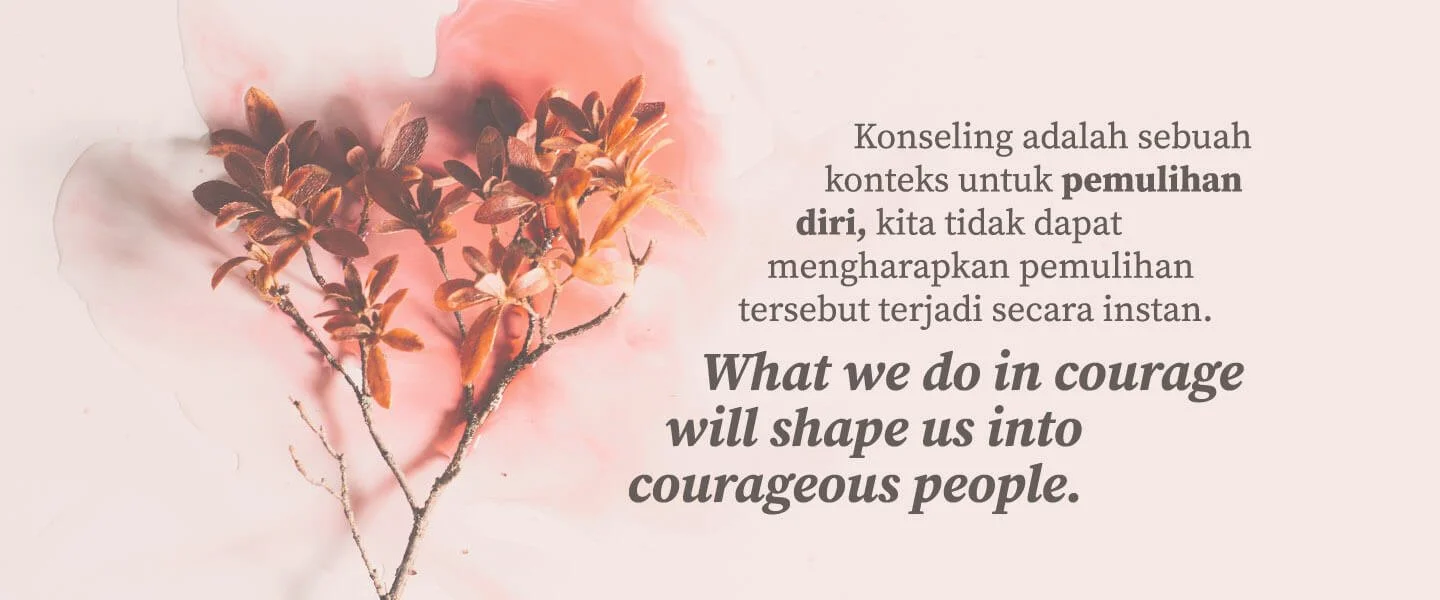Oversharing di Sosmed, Bijakkah?
by Tabita Davinia Utomo
Tujuh tahun yang lalu, ketika saya mulai kuliah di jurusan psikologi, isu kesehatan mental masih belum dilihat sebagai hal yang penting di kalangan banyak orang. Bahkan, beberapa orang sempat mempertanyakan keputusan saya, “Kenapa ambil psikologi? Nanti ngurusin orang sakit jiwa, lho!”
Namun, saya bersyukur karena saat ini isu kesehatan mental sudah lebih “disambut” oleh masyarakat. Mereka mulai menyadari bahwa ada banyak faktor yang membentuk kepribadian seseorang, sehingga stigma “gila” dan “sakit jiwa” perlahan-lahan tidak dilabelkan secara sembarangan. Berbagai konten di media sosial membantu edukasi mengenai pentingnya kesehatan mental. Selain itu, sarana pertolongan psikologis juga semakin berkembang. Salut untuk semua pekerja di bidang kesehatan mental yang sudah mendedikasikan dirinya untuk mengangkat isu ini!
Walaupun demikian, maraknya konten edukasi tentang kesehatan mental tidak menjamin bahwa seseorang akan menggunakannya dengan bijak. Ada kalanya mereka justru menjadikannya sebagai pembelaan di media sosial, misalnya dengan mengunggah situasinya secara berlebihan demi mendapatkan simpati orang lain. Ada juga yang melakukannya karena tidak memiliki support system di sekitarnya, sehingga mereka menjadikan media sosial sebagai tempat curhat. Well, tidak salah untuk berbagi di media sosial, tetapi jika dilakukan secara berlebihan, kita perlu mengevaluasi diri, nih. Kita ini kenapa? Kadang-kadang, kita tidak sadar bahwa sikap dan tindakan kita bisa membuat orang lain ilfeel, kan?
Jika Pearlians melihat fenomena ini (atau malah mengalaminya sendiri), kita perlu mengingat beberapa hal berikut:
1. Oversharing di sosial media tidak benar-benar menolong kita.
Seperti ketika berbicara secara tatap muka (atau melalui telepon maupun chat), ada kalanya berbagi di media sosial berguna untuk mengedukasi orang lain tentang isu yang sedang terjadi maupun topik yang jadi minat kita. Namun, bukan berarti kita dapat dengan sembarangan membagikan beban hidup—bahkan seluruh aspek kehidupan— kita pada orang lain. Tidak semua orang siap dengan apa yang kita bagikan. Salah-salah, mereka justru risih dan berasumsi negatif.
Ketika menghadapi tantangan kehidupan ini—studi yang macet, keuangan yang menipis, keluarga yang terus berkonflik, pernikahan yang diwarnai perselingkuhan—ada kalanya kita putus asa dan ingin melarikan diri ke media sosial yang menjadi wadah pengaduan kita. Karena merasa diperhatikan dan dipahami (atau malah tidak ada yang mengomeli balik), tanpa sadar ada banyak keluhan yang dibagikan di sana. Well, to be honest, oversharing di media sosial hanya dapat menolong kita “melampiaskan” sementara emosi yang berkecamuk, tetapi ini bukanlah jalan keluar utama dari pergumulan kita. Jika demikian, apa bedanya kita dari orang bukan percaya jika hidup kita tidak menunjukkan adanya pengharapan di dalam Tuhan? Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus berkata demikian di dalam Matius 11:28-30:
“Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun ringan”?
Jika kita benar-benar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, masihkah ada alasan bagi kita untuk meragukan kehadiran-Nya yang sanggup memulihkan jiwa kita yang lelah?
2. Carilah pertolongan di tempat yang tepat.
Sering kali, media sosial menjadi tempat untuk cry for help – mencari pertolongan – dari orang-orang yang bergumul dengan kesehatan mental. Iya, karena media sosial seolah-olah adalah tempat terbaik untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang lain. Namun, tidak semua masalah bisa diselesaikan “hanya” dengan membagikan pergumulan kita di sana. Memang benar kita membutuhkan orang lain sebagai sebagai support system, dan tidak ada salahnya untuk berbagi perasaan serta pikiran di sana. Walaupun demikian, apakah hanya ini satu-satunya cara untuk mendapatkan pertolongan bagi kondisi psikologis kita? Tentu saja tidak.
Menulis diary dapat menolong, betul. Pergi rehat sejenak juga tidak ada salahnya. Namun, kita juga harus menyadari bahwa sebagai manusia yang berdosa, kita tidak dapat menolong diri sendiri. Seorang konselor bahkan hamba Tuhan pun membutuhkan anugerah Tuhan untuk menghadapi pergumulan yang menghadang. Itulah alasan Paulus menulis Galatia 6:2, “Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikian kamu memenuhi hukum Kristus.” Amsal 17:17 pun menuliskan hal senada. Salah satu sarana yang Tuhan sediakan adalah melalui pelayanan konseling. Karena konseling adalah sebuah konteks untuk pemulihan diri, kita tidak dapat mengharapkan pemulihan tersebut terjadi secara instan. But remember: what we do in courage will shape us into courageous people.
3. Ingatlah identitasmu yang sesungguhnya.
Pada zaman kehidupan Yesus, garam dan terang temasuk dua hal pokok bagi orang Yahudi. Iyalah, tanpa garam, makanan menjadi hambar; tanpa terang, mereka tidak bisa melihat di dalam kegelapan. Identitas serupa juga dilekatkan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita adalah—bukan hanya sedang diproses untuk menjadi—garam dan terang dunia (Matius 5:13-16). Salah satu cara bagi kita membagikan “rasa” dan “cahaya” itu adalah melalui kata-kata maupun reaksi kita di media sosial. Well, orang-orang yang terkoneksi dengan kita di media sosial akan mencerminkan APA dan SIAPA yang menjadi tumpuan hidup kita. Jika kita bukanlah orang percaya yang melihat media sosial kita, akankah kita menemukan Kristus yang menjadi tumpuan hidup di dalamnya?
Saya setuju bahwa media sosial adalah salah satu sarana untuk menunjukkan keberadaan diri kita. Atau setidaknya, pemakaian media sosial menandakan bahwa kita masih hidup. Namun, bijakkah jika kita mem-posting konten yang membicarakan tentang “masalahKU”, “pergumulanKU”, “suicidal attemptsKU”, dan apa pun yang bertujuan menjadikan “AKU” sebagai pusat perhatian orang lain?
Kiranya Tuhan berbelas kasihan pada kita, para pengguna media sosial yang rapuh ini.